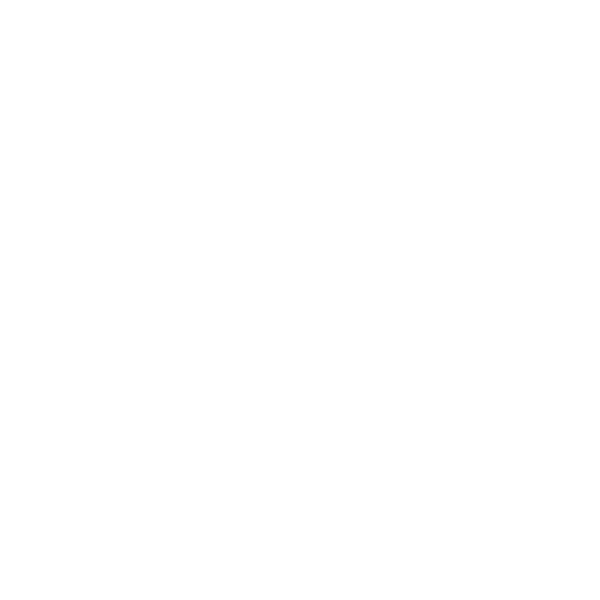Sarira itu tubuh. Kata ‘mulat’ dalam bahasa Kawi berarti melihat. Jadi, ‘kembali mulat sarira’ ialah kembali melihat tubuh. Jargon ‘mulat sarira’ seringkali disinonimkan dengan ‘introspeksi diri’. Tubuh dan diri seringkali diperlakukan sama, padahal sekaligus berbeda. Masalahnya adalah bagaimana menyamakan sekaligus membedakan keduanya.
Oleh karena bertubuh maka mampu berdiri. Ia yang terampil menubuh disebut mandiri. Jadi, tubuh adalah sebab, diri adalah akibat. Menubuh atau bersetubuh itu luar biasa nikmatnya, karena di situ ada segala rasa, campuhan rasa. Teks-teks tattwa kuno juga berkata demikian. Semisal, ketika berkendara, terjadi persetubuhan antara pengendara dengan kendaraan. Begitu nikmatnya berkendara hingga disebut lupa diri sedang berkendara, seperti dalam kalimat, “Saya ngebut tadi lho!” Tidak ada jarak antara pengendara dengan motornya. Dalam posisi itu, kata ‘saya’ berarti diri dan tubuh. Berbeda halnya jika, “Saya berkendara ngebut tadi lho!”, tapi kalimat ini terlalu kaku diujarkan.
Keadaan ini disebut pengalaman estetis yang berpuncak pada peristiwa ekstase, lango, lupa diri. Keadaan ini mirip seperti yang digambarkan Claire Holt (2000:122) sebagai “ketiadaan yang terkonsentrasi, seperti tidak yang dikejar para seniman, yang kemudian diekspresikan dalam suatu ciptaan, karya (struktur). Jadi, menubuh atau bersetubuh adalah sebab kehadiran sesuatu, lingga harus menubuh dalam yoni dalam lupa untuk menghadirkan suatu ciptaan.
Kemudian, pembedaan atau penjarakan diri dengan (tubuh) kendaraan terjadi ketika kendaraan mengalami masalah, misalnya, “Motor saya bannya pecah”. Begitu juga dengan tubuh, “Tangan saya kotor”; “Tangan saya sakit terkena pisau”; “Kaki saya patah”. Artinya, tubuh hanya diberi kesempatan memperlihatkan dirinya secara subjektif ketika ia mengalami masalah, itupun dengan tetap dikontrol pronomina posesif saya’, tetapi sudah membedakan. Alain Badiou (2018) menyatakan, “Kalau kamu ingin hidupmu punya makna, kamu harus tetap berada dalam suatu jarak dari kekuasaan.” Artinya, dalam situasi keberjarakan atau perbedaan itulah dimungkinkan terjadinya pemaknaan. Inilah yang disebut fase etis yang memungkinkan momen’ untuk memilih, ingat dengan kebertubuhan, lalu melakukan sesuatu seperti, membiarkan atau membersihkan dan mengobati tubuh itu.
Dengan demikian, diri harus berjarak dengan tubuh untuk memberinya peluang subjektif secara kebahasaan. Lalu, bagaimana mungkin terdapat dua subjek? Artinya, ketika dua subjek terbentuk, terdapat peluang saling mengobjekkan satu sama lain, saling melihat satu sama lain, saling mengadakan. Sehingga, dengan begitu terdapat bahasa, “Itu adalah aku.” Karena sejatinya diri bersifat subjektif, maka tugas berat yang harus dilakukan adalah meletakkan diri pada posisi objek. Dengan mengobjekkan diri, dimungkinkan peristiwa diri menguasai diri, memerintah diri, mengkritik diri, bahkan membunuh diri.
Cara tradisional untuk mengobjekkan diri atau paling tidak dapat dikatakan sebagai suatu cara latihan pengobjekan adalah dengan mewujudkan diri menjadi suatu objek di luar diri, yang seringkali disebut ‘simbolisasi’ atau ‘pangawak’. Para kawi mewujudkan diri dalam sastra adiluhung seringkali dengan nama samaran sebagai penanda “bunuh diri’’ secara puitis. Para anak muda mengekspresikannya dalam wujud ‘ogoh-ogoh’. Analogi ini juga mengisyaratkan bahwa kata ‘mulat’ juga identik dengan kata bahasa Bali ‘(ma)ulat’, menjalin ikat. Mudahnya, ogoh-ogoh tidak ubahnya salah satu pemurtian diri dengan cara mulat, refleksi lihat saja wajah dan bentuk ogoh-ogoh seringkali mirip pembuatnya-umumnya berbentuk demonik.
Posisi subjek tidak pemah bisa dilepaskan dari suatu pengobjekan; diri sebagai subjek melihat diri sebagai objek yang sekaligus subjek yang juga mengobjekkan dengan memakai kata ganti orang ketiga, “ia melakukan sesuatu terhadap sesuatu”. Cara mengobjekkan diri paling mudah selanjutnya adalah dengan bercermin. Dengan bercermin, kita melihat bayangan diri dan bentuk tubuh. Bayangan di cermin itu disebut refleksi. Tentu saja, refleksi pada cermin bersifat terbalik antara kiri-kanan dan menampilkan satu sisi saja. Untung saja tidak membalik antara atas dan bawah, tetapi paling tidak sudah mampu melihat diri.
Namun, semakin jauh dari cermin diri terlihat makin kecil, namun makin utuh. Mirip dengan selfie atau swafoto dan swavideo. Selanjutnya, cara lain adalah dengan mengandalkan logika, perbandingan, dan kata para nabi. Sekali lagi, itu juga terbatas.
Cara yang paling sulit adalah dengan menutup mata (baca: indera) dan membayangkan diri dalam meditasi. Mata terpejam artinya menarik diri dari luar dan memungkinkan imajinasi. Agama menyarankan, ketika menutup mata imajinasikanlah Tuhan, penguasa jagat raya, dewa idola, istadewata. Apakah lalu kita mengobjekkan Tuhan? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Iya, ketika posisi kesadaran memuja, “Aku memuja Tuhan”. Tidak, ketika dalam posisi mensubjekkan, “Tuhan datang dan memberkatiku.” Juga tanpa keduanya, posisi setara, “aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku”.
Situasi mata terpejam hampir sama dengan sedang tidur lalu bermimpi. Di dalam mimpi kita bisa melihat diri sedang melakukan apa terhadap apa. Namun, kata ‘mimpi’ selalu diidentikkan dengan keadaan bawah sadar atau ketidaksadaran. Padahal, menurut Freud, dalam mimpilah pengalaman melihat diri yang sejak lama direpresi oleh kesadaran. Dalam mimpi juga, diri sejati dapat dialami, diri yang melihat diri yang jujur atau tanpa represi.
Setelah itu, apakah kita terus-menerus memejamkan mata dalam meditasi atau bermimpi agar dapat melihat diri yang jujur? Dalam meditasi ternyata ada jebakan ‘lupa diri’ tadi, lupa makan, lupa minum, lupa mendunia, lupa daratan, dan tentu saja lupa sedang menjadi manusia. Di situlah jargon mulat sarira memegang posisi kunci sebagai epistemologi Bali; tubuh sebagai gudang pengetahuan. Mulat sarira juga kritik terhadap doktrin pencerahan, cogito ergo sum, akal sebagai pusat pengetahuan yang mengesampingkan tubuh.
Mulat sarira memungkinkan terkikisnya jarak antara mata terpejam dan terbuka, setengah terbuka setengah terpejam; mengecilnya jarak mimpi dan realitas; jarak tidur dan sadar; jarak ketidaksadaran dengan kesadaran menipis. Semakin menipis lalu manunggal. Itulah klimaks, segala objek yang diwujudkan, diimajinasikan, “dibunuh” secara religius, termasuk diri yang lain dan Tuhan yang diobjekkan, ogoh-ogoh pun dibakar. Yang tinggal hanya diri se-ati, diri yang jujur, diri yang sepi, diri yang religius. Diri kembali kepada tubuh, menyatu bersatu padu tanpa sekat dalam mulat sarira dan manusia kembali pada kemanusiaannya.
Oleh: W.A. Sindhu Gitananda
Source: Majalah Wartam Edisi 48 l Februari 2019